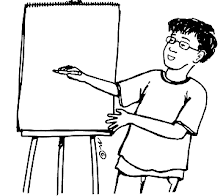BAB I
PENDAHULUAN
PENGANTAR MASA REMAJA
Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah (Hurlock, 1998). Oleh karenanya, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial.
Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah (atau sedang) mengalami pubertas namun tidak berarti ia sudah bisa dikatakan sebagai remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. Ia belum siap menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski di saat yang sama ia juga bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang perkembangannya dengan jelas dapat diukur, remaja hampir tidak memiliki pola perkembangan yang pasti. Dalam perkembangannya seringkali mereka menjadi bingung karena kadang-kadang diperlakukan sebagai anak-anak tetapi di lain waktu mereka dituntut untuk bersikap mandiri dan dewasa.
Hurlock (1973) memberi batasan masa remaja berdasarkan usia kronologis, yaitu antara 13 hingga 18 tahun. Menurut Thornburgh (1982), batasan usia tersebut adalah batasan tradisional, sedangkan aliran kontemporer membatasi usia remaja antara 11 hingga 22 tahun.
Lebih lanjut Thornburgh membagi usia remaja menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Remaja awal : antara 11 hingga 13 tahun
b. Remaja pertengahan: antara 14 hingga 16 tahun
c. Remaja akhir: antara 17 hingga 19 tahun.
Pada usia tersebut, tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
1. Mencapai hubungan yang baru dan lebih masak dengan teman sebaya baik sesama jenis maupun lawan jenis
2. Mencapai peran sosial maskulin dan feminin
3. Menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara efektif
4. Mencapai kemandirian secara emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya
5. Mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi
6. Memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja
7. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga
8. Mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi sebagai warga negara
9. Menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial
10. Memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman perilaku (Havighurst dalam Hurlock, 1973).
Tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas tersebut dengan baik. Menurut Hurlock (1973) ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu:
1. Masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas dan nilai-nilai.
2. Masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orangtua.
Memang banyak perubahan pada diri seseorang sebagai tanda keremajaan, namun seringkali perubahan itu hanya merupakan suatu tanda-tanda fisik dan bukan sebagai pengesahan akan keremajaan seseorang. Namun satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka.
Untuk dapat memahami remaja, maka perlu dilihat berdasarkan perubahan pada dimensi dimensi tersebut.
- DIMENSI BIOLOGIS. Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri atau pun perubahan suara pada remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar.
- DIMENSI KOGNITIF. Perkembangan kognitif remaja, dalam pandangan Jean Piaget (seorang ahli perkembangan kognitif) merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal (period of formal operations). Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya.
- DIMENSI MORAL. Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanyamengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Elliot Turiel (1978) menyatakan bahwa para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalahmasalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dsb. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangan lebih banyak alternatif lainnya.
- DIMENSI PSIKOLOGIS. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini mood (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian di Chicago oleh Mihalyi Csikszentmihalyi dan Reed Larson (1984) menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 45 menit untuk berubah dari mood “senang luar biasa” ke “sedih luar biasa”, sementara orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan mood (swing) yang drastis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Dalam hal kesadaran diri, pada masa remaja para remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka (self-awareness). Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka menganggap bahwa orang lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mereka mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Anggapan itu membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka dan citra yang direfleksikan (self-image). Remaja cenderung untuk menganggap diri mereka sangat unik dan bahkan percaya keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran.
Dari penjelasan di atas, kita sudah mengetahui masalah-masalah remaja yang sering kita temui pada remaja,tapi dalam pembahasan di dalam makalah ini adalah depresi, dimana depresi ini sangat mempengaruhi semua aspek perkembangan pada remaja. Dan oleh karena itu dalam bab selanjutnya akan membahas depresi dan pengaruhnya terhadap perkembangan mental remaja dan dampaknya sehingga remaja memilih untuk bunuh diri sebagai solusi.
BAB II
PEMBAHASAN MASALAH
Dalam kehidupan remaja banyak sekali permasalahan yang dapat kita temui pada remaja, seperti penggunaan dan penyalahgunaan obat terlarang, kenakalan remaja, depresi, bunuh diri, dan lain-lain.
Di makalah ini akan membahas depresi pada remaja yang mengakibatkan dia memilih untuk bunuh diri, berikut penjelasannya.
I. PENGERTIAN DEPRESI
Depresi adalah suatu gangguan keadaan tonus perasaan yang secara umum ditandai oleh rasa kesedihan, apati, pesimisme, dan kesepian. Keadaan ini sering disebutkan dengan istilah kesedihan (sadness), murung (blue), dan kesengsaraan. Pada orang normal merupakan ganguan kemurungan (kesedihan, patah semangat) yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang, pada kasus patlogis, merupaan ketidakmauan ekstrim untuk mereaksi terhadap rangsang disertai menurunnya nilai diri, delusi ketidakpasan, tidak mampu, dan putus asa.
Depresi adalah gangguan yang memiliki karakteristik:
a. Gejala Utama
Ø Afek depresif
Ø Kehilangan minat dan kegembiraan
Ø Berkurangnya energi yang menuju pada meningkatnya keadaan mudah lelah (rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan menurunnya aktifitas.
b. Gejala lainnya
Ø Konsentrasi dan perhatian berkurang
Ø Harga diri dan kepercayaan diri berkurang
Ø Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna
Ø Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis
Ø Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri
Ø Tidur terganggu
Ø Nafsu makan berkurang
Depresi menurut DSM IV dapat 3 kategori, yaitu:
1. Gangguan depresi berat (Mayor diklasifikasikan dalam depressive disorder). Mensyaratkan kehadiran 5 atau lebih simptom depresi menurut kriteria DSM-IV selama 2 minggu. Kriteria terebut adalah:
a. Suasana perasaan depresif hampir sepanjang hari yang diakui sendiri oleh subjek ataupun observasi orang lain. Pada anak-anak dan remaja perilaku yang biasa muncul adalah mudah terpancing amarahnya.
b. Kehilangan interes atau perasaan senang yang sangat signifikan dalam menjalani sebagian besar aktivitas sehari-hari.
c. Berat badan turun secara siginifkan tanpa ada progran diet atau justru ada kenaikan berat badan yang drastis.
d. Insomnia atau hipersomnia berkelanjutan.
e. Agitasi atau retadasi psikomotorik.
f. Letih atau kehilangan energi.
g. Perasaan tak berharga atau perasaan bersalah yang eksesif.
h. Kemampuan berpikir atau konsentrasi yang menurun.
i. Pikiran-pikiran mengenai mati, bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang muncul berulang kali.
j. Distres dan hendaya yang signifikan secara klinis.
k. Tidak berhubugan dengan belasungkawa karena kehilangan seseorang.
2. Gangguan distimik (Dysthymic disorder) Suatu bentuk depresi yang lebih kronis tanpa ada bukti suatu episode depresi berat. Dahulu disebut depresi neurosis. Kriteria DSM-IV untuk gangguan distimik:
a. Perasaan depresi seama beberapa hari, paling sedikit selama 2 tahun (atau 1 tahun pada anak-anak dan remaja)
b. Selama depresi, paling tidak ada dua hal berikut yang hadir: tidak nafsu makan atau makan berlebihan, insomnia atau hipersomnia, lemah atau keletihan, self esteem rendah, daya konsentrasi rendah, atau sulit membuat keputusan, perasaan putus asa.
c. Selama 2 tahun atau lebih mengalami gangguan, orang itu tanpa gejala-gejala selama 2 bulan.
d. Tidak ada episode manik yang terjadi dan kriteria gangguan siklotimia tidak ditemukan.
e. Gejala-gejala ini tidak disebabkan oleh efek psikologis langsung darib kondisi obat atau medis.
f. Signifikansi klinis distress (hendaya) atau ketidaksempurnaan dalam fungsi.
3. Gangguan afektif bipolar atau siklotimik (Bipolar affective illness or cyclothymic disorder). Kriteria menurut DSM-IV:
a. Kemunculan (atau memiliki riwayat pernah mengalami) sebuah sebuah episode depresi berat atau lebih.
b. Kemunculan (atau memiliki riwayat pernah mengalami) paling tidak satu episode hipomania.
c. Tidak ada riwayat episode manik penuh atau episode campuran.
d. Gejala-gejala suasan perasaan bukan karena skizofrenia atau menjadi gejala yang menutupi gangguan lain seprti skizofrenia.
e. Gejala-gejalanya tidak disebabkan oleh efek-efek fisiologis dari substansi tertentu atau kondisi medis secara umum.
f. Distres atau hendaya dalam fungsi yang signifikan secara klinis.
II. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DEPRESI
Secara umum orang mengalami depresi karena salah satu kejadian atau situasi sebagai berikut:
1. Kesan pada tubuh dan gangguan makanan
2. Perselisihan dan inkonsistensi
3. Disiplin keluarga yang tidak sesuai
4. Norma dari kelompok-kelompok dan geng-geng teman sebaya
5. kehilangan orang yang dicintai, mungkin karena kematian
6. peristiwa traumatis atu stressfull, misalnya mengalami kekerasan, deprifasi sosial yang kronik atau penolakan sosial.
7. Penyakit fisik yang kronis
8. Obat- obatan atau narkoba
9. Adanya penyakit mental lain
10. Seseorang yang mempunyai orang tua atau saudara kandung yang mengalami depresi akan mengalami peningkatan resiko mengalami depresi juga.
Faktor- faktor lain yang dapat menyebabkan depresi antara lain adalah:
- Faktor genetik. Meskipun penyebab depresif secara pasti tidak dapat ditentukan, faktor genetik mempunyai peran terbesar. Gangguan alam perasaan cenderung terdapat dalam suatu keluarga tertentu. Bila suatu keluarga salah satu orang tuanya menderita depresi, maka anaknya beresiko dua kali lipat akan menderita depresi juga. Apabila kedua orang tuanya menderita depresi, maka resiko untuk mendapatkan gangguan alam perasaan sebelum usia 18 tahun menjadi 4 kali lipat.
- Faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kehilangan sesuatu, stress, mungkin bisa jadi variabel penyebab yang terpenting. Karena depresi dapat timbul pada keluarga, anak-anak yang depresi lebih sering ditemukan pada keluarga atau orang tua yang mengalami depresi (lebih sering pada ibu). Interaksi ibu-ibu yang depresi pada anak-anaknya bisa berakibat negatif. Depresi juga bisa muncul karena salah asuh di rumah. Anak yang mendapat perlakukan tidak mengenakan dari orangtua cendrung mudah marah dan tidak puas. Tapi anak tidak tahu cara pelampiasannya sehingga mereka melampiaskan ke dirinya sendiri.
III. MENANGANI DEPRESI PADA REMAJA
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi depresi pada remaja, antara lain:
- Peran orang tua, dimana orang tua harus:
- menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak prenatal dan balita
- membekali anak dengan dasar moral dan agama
- menjalin kerjasama yang baik dengan guru.
- Peran guru
1. bersahabat dengan siswa
2. menciptakan kondisi sekolah yang nyaman
3. meningkatkan kerja sama dengan orangtua, sesama guru dan sekolah lain
4. memberikan keteladanan
5. menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menampung agresifitas anak melalui olah raga dan bermain.
- Peran media
1. sajikan tayangan atau berita tanpa kekerasan ( jam tayang sesuai usia)
2. sampaikan berita dengan kalimat yang benar dan tepat (tidak provokatif)
IV. BUNUH DIRI
Bunuh diri merujuk kepada perbuatan memusnahkan diri karena enggan berhadapan dengan sesuatu perkara yang dianggap tidak dapat ditangani. Menurut Keliat (1994) bunuh diri adalah tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan dan merupakan keadaan darurat psikiatri karena individu berada dalam keadaan stres yang tinggi dan menggunakan koping yang maladaptif. Lebih lanjut menurut Keliat, bunuh diri merupakan tindakan merusak integrasi diri atau mengakhiri kehidupan, di mana keadaan ini didahului oleh respon maladaptif dan kemungkinan keputusan terakhir individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Orang yang melakukan tindakan bunuh diri mempunyai pikiran dan perilaku yang merupakan perwakilan (representing) dari kesungguhan untuk mati dan juga merupakan manifestasi kebingungan (ambivalence) pikiran tentang kematian (Hoeksema, 2001).
Wilkinson (1989) membedakan antara bunuh diri dengan usaha bunuh diri. Wilkinson, menyebutkan jika bunuh diri merupakan tindakan merusak diri yang disengaja oleh seseorang yang menyadari apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Sementara usaha bunuh diri merupakan tindakan yang tidak fatal, paling sering melibatkan masalah dosis obat berlebihan (terutama obat pengubah suasana hati) tetapi dapat juga melibatkan berbagai jenis melukai diri sendiri.
Shneidman (dalam Barlow dan Durand, 2002) membedakan bunuh diri berdasarkan individunya ke dalam empat tipe. Berikut empat tipe bunuh diri menurut Shneidman :
- Pencari Kematian (Death Seekers). Individu-individu yang termasuk dalam tipe ini adalah individu yang secara jelas dan tegas mencari dan menginginkan untuk mengakhiri kehidupannya. Kesungguhan mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri, sudah hadir dalam jangka waktu yang lama, mereka telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kematian mereka. Mereka telah memberikan barang-barang milik mereka kepada orang lain, menuliskan keinginan mereka, membeli sepucuk pistol, lalu segera bunuh diri. Selanjutnya, kesungguhan mereka akan berkurang, dan jika mereka gagal melakukan bunuh diri, mereka kemudian menjadi ragu atau kebingungan (ambivalent) dalam memutuskan untuk mati.
- Inisiator Kematian (Death Initiators). Inisiator-inisiator mati juga mempunyai keinginan yang jelas untuk mati, tetapi mereka percaya jika kematian mau tidak mau akan segera mereka rasakan. Individu yang menderita penyakit serius tergolong ke dalam tipe ini. Sebagai contoh, beberapa penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus), sebelum mereka mendapatkan perawatan, baik itu perawatan medis atau bukan, terlebih dahulu memutuskan untuk bunuh diri. Hal ini mereka lakukan dengan pertimbangan bahwa mati lebih baik dari pada harus menghadapi penyakit mereka yang mau tidak mau akan bertambah parah dan kemungkinan berubah menjadi AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).
- Pengabai Kematian (Death Ignorers). Bersungguh-sungguh untuk mengakhiri kehidupannya, tapi mereka tidak percaya jika keinginan tersebut merupakan akhir dari keberadaan (existence) dirinya. Mereka meyakini bahwa mati merupakan awal dari kehidupan mereka yang baru dan lebih baik. Kelompok-kelompok keagamaan tertentu termasuk ke dalam kategori ini. Sebagai contoh, pada tahun 1997, 39 orang anggota Heaven’s Gate cult melakukan bunuh diri massal.
- Penantang Kematian (Death Darers). Ragu-ragu (Ambivalent) dalam memandang kematian, dan mereka bertindak jika kesempatan untuk mati bertambah besar. Tetapi hal tersebut, bukanlah suatu jaminan jika mereka akan mati. Orang-orang yang menelan segenggam obat atau pil tanpa mengetahui seberapa berbahaya obat atau pil tersebut, kemudian memanggil seorang teman, tergolong ke dalam tipe ini. Anak-anak muda yang secara acak memasukkan sebuah peluru ke dalam pistol, kemudian mengarahkan ke kepala mereka juga termasuk ke dalam tipe ini. Orang-orang yang termasuk Death Darers, adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian atau membuat seseorang atau orang lain merasa bersalah. Dan hal tersebut, melebihi keinginan mereka untuk mati.
Menurut Durkheim (dalam Lyttle, 1986 & Nevid., dkk., 1997) yang konsern mengkaji bunuh diri dengan menggunakan perspektif sosiologi, menyebutkan jika bunuh diri terdiri atas beberapa prinsip tipe. Beberapa prinsip tipe tersebut adalah :
- Anomic Suicide. Kondisi ketidaknormalan individu berada pada posisi yang sangat rendah, individu adalah orang yang terkatung-katung secara sosial. Anomic suicide adalah hasil dari adanya gangguan yang nyata. Sebagai contoh, seseorang yang tiba-tiba harus kehilangan pekerjaannya yang berharga kemudian melakukan tindakan bunuh diri termasuk ke dalam tipe ini. Anomie disebut juga kehilangan perasaan dan menjadi kebingungan.
- Egoistic Suicide. Kekurangan keterikatan dengan komunitas sosial atau masyarakat, atau dengan kata lain individu kehilangan dukungan dari lingkungan sosialnya atau masyarakat. Sebagai contoh, orang-orang yang sudah lanjut usia (elderly) yang membunuh diri mereka sendiri setelah kehilangan kontak atau sentuhan dari teman atau keluarganya bisa dimasukkan ke dalam kategori ini.
- Altruistic Suicide. Pengorbanan diri (self-sacrifice) sebagai bentuk peran serta sosial dan untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat, sebagai contoh kamikaze atau seppuku di jepang. Tipe ini disebut juga “formalized suicide”
- Fatalistic Suicide. Merupakan bunuh diri sebagai akibat hilangnya kendali diri dan merasa jika bisa menentukan takdir diri sendiri dan orang lain. Bunuh diri massal yang dilakukan oleh 39 orang anggota Heaven’s Gate cult adalah contoh dari tipe ini. Kehidupan 39 orang ini berada di tangan pemimpinnya.
Penyebab terjadinya bunuh diri sangat beragam dan sebagian besar perilaku tersebut dilatar belakangi ketidakmampuan ekonomi, namun faktor pencetusnya atau pemicunya bisa masalah keluarga, sakit, atau masalah dengan pasangan.
V. STUDI KASUS
 Berikut contoh studi kasus mengenai depresi yang pada akhirnya memilih bunuh diri sebagai solusi.
Berikut contoh studi kasus mengenai depresi yang pada akhirnya memilih bunuh diri sebagai solusi.
DEPRESI KARENA TIDAK MASUK PTN, SEORANG PEMUDA BAKAR DIRI

Kamis, 2 Juli 2009 |
Laporan wartawan KOMPAS Ratih P Sudarsono
Depresi karena tidak masuk perguruan tinggi negeri atau disingkat dengan PTN, Abdul Majid (18) tewas membakar diri di kamar tidur di rumah adiknya di Perumnas II Parung Panjang,
”Pihak keluarga tidak mengizinkan jasadnya diotopsi. Mereka menyatakan ikhlas karena korban memang menderita depresi dan berkali-kali mencoba bunuh diri,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Parung Panjang Iptu Ida Bagus Kade Dayana.
 Menurut Ida Bagus, tetangga korban, Hasanuddin, yang pertama kali melihat rumah Ida (25) terbakar. Hasanuddin tahu setelah api yang membakar rumah Ida mulai menyambar rumahnya. Ida, adik Abdul Majid, saat itu tidak ada di rumah karena sedang ikut pengajian..
Menurut Ida Bagus, tetangga korban, Hasanuddin, yang pertama kali melihat rumah Ida (25) terbakar. Hasanuddin tahu setelah api yang membakar rumah Ida mulai menyambar rumahnya. Ida, adik Abdul Majid, saat itu tidak ada di rumah karena sedang ikut pengajian..
Warga lalu beramai-ramai memadamkan api. Setelah api padam, baru mereka menemukan jasad Abdul Majid di dalam kamar tidur yang sudah terbakar. ”Kebakaran diduga berasal dari kamar itu, setelah korban membakar dirinya dengan menggunakan bensin,” kata Ida Bagus. Keluarga korban lalu membawa pulang jasad Abdul Majid ke rumah orangtuanya di Puri Kembangan, Jakarta Barat.
VI. PEMBAHASAN STUDI KASUS
Ketika berbicara kesuksesan dan atau kegagalan dalam hidup maka berjalan bagai roda pedati yang bergantian menghinggapi manusia. Apalagi jika menengok pada ayat Allah dalam Alquran “bahwa bersama kesulitan itu, ada kemudahan” sehingga jika orang meyakini kebenaran ayat ini akan menghadapi kegagalan tanpa keraguan. Dalam kasus diatas, kita dapat membahasnya berdasarkan Teori Kognitf – Behavior dan berdasarkan Dimensi Psikologi. Berikut penjelasannya:
Teori kognitif-behavior meyakini jika kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap memberikan kontribusi terhadap terjadinya perilaku bunuh diri. Konsistensi prediksi yang tinggi dari variabel kognitif terhadap bunuh diri adalah kehilangan harapan (hopelessness), perasaan jika masa depan sangatlah suram dan tidak ada jalan untuk menjadikan hal tersebut menjadi lebih baik atau positif (Beck, dkk., dalam Hoeksema, 2001). Adanya pemikiran yang bercabang (dichotomous thinking), kekakuan dan ketidak luwesan dalam berpikir menjadi penyebab seseorang bunuh diri. Kekakuan dan ketidak luwesan tersebut menjadikan seseorang kesulitan dalam menemukan alternatif penyelesaian masalah sampai perasaan untuk bunuh diri yang dirasakan oleh orang tersebut menghilang. Karakteristik perilaku yang menunjukkan atau yang menjadi penyebab seseorang melakukan bunuh diri adalah impulsifitas. Perilaku ini (impulsif), akan semakin berisiko jika terkombinasikan dengan gangguan psikologis yang lain, seperti depresi atau tinggal di lingkungan dengan potensi untuk menghasilkan stres yang tinggi (Hoeksema, 2001). Dalam hal ini perlu juga yang namanya kecerdasan emosi dalam menghadapi kegagalan. Kecerdasan intelektual yang dimiliki boleh jadi membuat kecerdasan emosinya terhambat. Sebab sibuk dengan dirinya sendiri dan merasa lebih bisa menyelesaikan problemnya tanpa harus melibatkan banyak orang. Adapun kecerdasan emosi merupakan kebutuhan vital manusia sebab kerabat kuat dalam otak. Dalam hal pekerjaan, Golman dan Cardver menyatakan bahwa kecerdasan emosi memiliki kontribusi 27-51 persen untuk keberhasilan pekerjaan seseorang. Dan ini yang membedakan dengan IQ yang berkontribsi 20 persen saja. Penyebab bunuh diri seperti kasus di atas menurut Hendlin adalah:
- Self-ideal terlalu tinggi
- Cemas akan tugas akademik yang banyak
- Kegagalan akademik berarti kehilangan penghargaan dan kasih sayang orang tua
- Kompetisi untuk sukses
Dalam antisipasi kegagalan dibutuhkan soliditas keluarga (ayah, ibu, saudara kandung) ketika terjadi kegagalan. Dalam arti bahwa setiap persoalan hendaknya dibicarakan dalam keluarga, baik itu besar ataupun kecil. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian untuk menciptakan lingkungan yang terbuka serta tidak menutup pula berkomunikasi kepada teman atau oaring yang dapat dipercaya dapat membantu menyelesaikan masalah.
Dimensi Psikologis Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini mood (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Perubahan mood (swing) yang drastis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Dalam hal kesadaran diri, pada masa remaja para remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka (self-awareness). Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka menganggap bahwa orang lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mereka mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Anggapan itu membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka dan citra yang direfleksikan (self-image). Remaja cenderung untuk menganggap diri mereka sangat unik dan bahkan percaya keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran.
BAB III
KESIMPULAN
Depresi dan kehilangan harapan, terlebih lagi jika keduanya terkombinasikan dengan self-esteem yang rendah, adalah faktor risiko dalam melakukan bunuh diri yang paling utama pada remaja dan juga pada orang dewasa. Studi yang dilakukan kepada anak-anak dan remaja menunjukkan jika depresi meningkatkan risiko untuk bunuh diri. Goodwin dan Jamison (dalam Hoeksema, 2001) mengatakan jika setengah dari individu dengan gangguan bipolar melakukan percobaan bunuh diri, dan kemungkinan satu dari lima sukses melakukan bunuh diri. Gangguan psikologis yang lain yang meningkatkan risiko untuk bunuh diri dan usaha bunuh diri adalah alkoholik dan penyalahgunaan narkoba (Statham, dalam Hoeksema, 2001). Semua bentuk gangguan psikologis atau gangguan mental berpotensi menjadi faktor risiko perilaku bunuh diri. Untuk mengurangi resiko bunuh diri pada remaja ini sangat perlu diperhatikan, dimana perhatian dari orangtua terhadap permasalahan anak harus lebih diperhatikan. Peran guru juga sangat penting dalam mengurangi dampak ini. Dimana guru harus menciptalan suasana belajar yang nyaman bagi sisiwa dan memberikan kehangatan bagi siswa. Anak juga harus dikontrol hubungannya terhadap media, dimana dalam media sungguh banyak sekali informasi-informasi baik yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian untuk menciptakan lingkungan yang terbuka. Serta tidak menutup pula berkomunikasi kepada teman atau orang yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan masalah. Dengan adanya perhatian-perhatian seperti itu, remaja akan dapat mengurangi masalah-masalahnya yang dapat menimbulkan depresi dan nanti mengakibatkan keperilaku bunuh diri dan yang pasti itu tidak kita inginkan. ”Semoga”.
DAFTAR PUSTAKA
Hurlock, E.B (1998). Perkembangan Anak. Alih bahasa oleh Soedjarmo & Istiwidayanti.
Atkinson (1999). Pengantar Psikologi.
Mappiare, A. (1992). Psikologi Remaja.
Kartono, K. (1981). Patologi Sosial.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fourth Edition.